KURUNGBUKA.com – Saya jarang menangis saat menonton film. Tetapi film Pangku membuat saya meneteskan air mata di momen-momen yang bahkan tidak seharusnya mengundang tangis. Ada sesuatu dalam cara film ini bercerita; lamban, sederhana, tapi menghantam tepat di dada dari gaya tuturnya yang begitu jujur. Saat lagu Rayuan Perempuan Gila milik Nadin Amizah diputar, saya menyerah. Air mata jatuh begitu saja. Dan entah kenapa, sampai pulang di atas motor ojek online pun, saya masih menangis. Pangku bukan sekadar tontonan, ia terasa seperti kenyataan yang dihadirkan di depan mata yang telanjang dan apa adanya.
Pangku bercerita tentang Sartika (Claresta Taufan), perempuan muda yang sedang mengandung dan memutuskan meninggalkan kampung halamannya demi mencari hidup baru untuk anaknya. Ia menumpang truk, berjalan tanpa arah menuju kawasan Pantura—wilayah yang juga terdampak oleh peristiwa krisis moneter di tahun 1998.
Dalam perjalanan itu, Sartika bertemu Bu Maya (Christine Hakim), pemilik warung kopi di tepi jalan Pantura. Bu Maya dikenal ramah dan suka menolong, tapi di balik senyum hangatnya tersembunyi maksud lain. Ia menampung Sartika yang hamil tua, merawatnya, bahkan membantu proses persalinan. Namun setelah bayi lahir, kebaikan itu seolah menuntut balas budi.

Sartika dibujuk untuk bekerja di warung sebagai pelayan “kopi pangku”—istilah yang terdengar remeh, tapi menyiratkan betapa perempuan sering kali tidak punya ruang untuk menolak. Di warung itu, pelayan tidak hanya menyuguhkan kopi, tapi juga ditemani pandangan dan sentuhan laki-laki yang haus perhatian. Sartika sempat menolak, tapi keadaan ekonomi dan beban menjadi ibu tunggal membuatnya terpaksa bertahan.
Hidup Sartika berubah jadi rutinitas yang menyesakkan. Namun di tengah kepahitan itu, ia bertemu Hadi (Fedi Nuril), sopir pick-up pengangkut ikan yang kerap singgah di warung Bu Maya. Pertemuan mereka sederhana saja sekadar obrolan singkat, menemani merokok, dan tatapan yang lama-lama menumbuhkan simpati. Hadi tampak jujur, lugu, dan polos pada mulanya. Ia melihat Sartika bukan sebagai pelayan “kopi pangku” tapi sebagai manusia yang sedang berjuang.

“Nyari kresek mah gampang, nyari bapak yang susah,” kata Bayu (Shakeel Fauzi), anak Sartika, dalam satu adegan yang tak akan saya lupakan. Dialog polos itu mengguncang kesadaran, karena diucapkan dengan kepolosan anak kecil yang sebenarnya tahu betul bagaimana dunia memperlakukan ibunya dan menunjukkan betapa tidak adilnya dunia karena tidak berpihak kepada hidup mereka. Akting Shakeel luar biasa memesona dan mengagumkan.
Awalnya saya berpikir film ini ingin menunjukkan bahwa kebaikan bisa tumbuh di tempat sekelam apa pun. Tapi menjelang akhir, saya justru marah pada Hadi dan pada kenyataan sesungguhnya. Ternyata tidak semua yang terlihat tulus benar-benar bisa diandalkan. Atau justru film ini ingin mengatakan bahwa manusia memang bersifat abu-abu. Di sisi lain Pangku begitu berani membiarkan luka itu sembuh dengan caranya sendiri.

Yang membuat Pangku istimewa bagi saya bukan hanya ceritanya, tapi bagaimana cara Reza Rahadian sebagai sutradara sekaligus penulis skenarionya yang dibantu oleh Felix K. Nesi berhasil menyusunnya dengan penuh empati. Mereka tahu kapan harus bercerita panjang tentang satu adegan, kapan cukup dengan satu simbol kecil. Misalnya, adegan pernikahan yang tidak perlu ditampilkan megah, cukup sebuah foto di dinding. Atau bagaimana film ini memainkan simbol di setiap adegan seperti korek api Hadi yang selalu hilang, seolah melambangkan seorang laki-laki yang tidak pernah benar-benar hadir dan bertanggung jawab.
Film ini juga menyinggung sesuatu yang sangat nyata: ketika Sartika kesulitan menyekolahkan Bayu karena tidak bisa mencantumkan nama dirinya di kolom “ayah”. Seketika saya turut merasakan kekecewaannya. Betapa sistem sosial bahkan di ranah pendidikan masih menganggap kehadiran seorang ibu saja tidak cukup dalam sebuah keluarga.

Dan saat film ditutup dengan lagu Ibu milik Iwan Fals, saya benar-benar tersungkur. Lagu itu, yang selama ini tidak pernah berhasil saya nyanyikan sampai habis karena selalu menangis di tengah bagian, menjadi pukulan telak terakhir yang membuat saya termangu cukup lama.
Dari sisi teknis, Pangku adalah karya yang nyaris sempurna. Detail era 1998-nya hidup—dari pakaian, warung, jalanan berdebu, bau ikan asin sampai aroma Pantura yang bau oli dan penuh keringat. Semuanya dibuat dengan hati-hati dan cinta yang tulus. Teoh Gay Hian, sang Director of Photography (DOP), menangkap dunia itu dengan kejujuran yang apa adanya dan segala keindahan sinema yang disuguhkan. Kameranya tidak menilai, tidak menghakimi, hanya menatap dengan tenang dan berhasil menceritakan seutuhnya. Seperti halnya Yuni, film lain yang juga ia tangani, Pangku berhasil menjadi potret realitas yang tenang tapi meninggalkan jejak cukup lama di kepala.

Yang paling saya kagumi, meski disutradarai dan ditulis oleh laki-laki, film ini terasa sangat feminin. Suara perempuan begitu jelas terdengar: tentang tubuh, pilihan, harga diri, dan keberanian untuk bertahan tanpa kehilangan marwahnya. Tidak ada yang ditampilkan secara murahan atau eksploitatif. Semua perempuan di film ini memiliki prinsip dan suara yang berharga.
Begitu pun setiap aktor yang hadir, entah besar atau kecil perannya, punya makna. Tidak ada yang terasa sia-sia. Semua berkontribusi terhadap perjalanan batin Sartika dan penonton.
Saya memberi nilai yang cukup tinggi untuk Pangku. Bukan karena film ini sempurna, tapi karena ia jujur dan berani. Ia membuat saya menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa film ini berhasil menyampaikan pesannya dengan sangat baik, bahwa perjuangan seorang ibu untuk anaknya di keadaan apa pun pasti akan habis-habisan bahkan melampaui kemampuannya sendiri. Di luar sana, banyak perempuan yang hidupnya mungkin serupa dengan Sartika: mencoba bertahan di dunia yang tidak memberinya banyak pilihan.

Reza Rahadian, lewat debut penyutradaraannya, membuktikan bahwa empati bisa lebih kuat dari sekadar narasi. Ia tidak membuat film tentang perempuan yang cerewet dan banyak menuntut, termasuk akting para aktornya pun minim sekali dialog tetapi rasanya berhasil ditransfer ke penonton dengan sangat baik. Ia membuat film untuk perempuan dan untuk siapa pun yang masih berusaha menjadi manusia di tengah dunia yang kejam dan tidak adil ini. Pangku bukan hanya film. Ia adalah pengalaman. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap tawa sesungguhnya ada luka yang begitu besar tengah dihadapinya seorang diri.
Skor: 9/10
*) Image by imdb.com



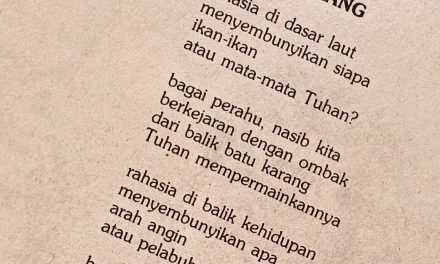














Setuju dengan semua yang ditulis Mas Ade. Film ini sangat menang di kejujuran, apa adanya, karena hidup orang-orang “kalah” ya begitu. Tidak ada pilihan selain menjalani seperti kata Mbok “Nggak usah dipikirin Tik, dijalani saja”. Bukan pilihan mereka untuk hanya menjalani, tapi karena memang itu satu-satunya pilihan yang mereka punya.