Sudah jelas aku menggunakan seragam SMA saat itu, namun masih dirasa pantas untuk dikatakan tak beradat oleh tiga orang tua dengan alasan yang aku pun sama sekali tak mengerti. Saat itu, sebagai salah satu perwakilan kelas kami pergi melayat ke rumah Rifai, teman sekelasku yang ayahnya meninggal dunia. Wali kelas kami masuk ke dalam rumah bersama dua orang temanku sedang aku memutuskan untuk tinggal di luar seorang diri. Aku sebenarnya telah memilih kursi yang kiri dan kanannya kosong untuk menghindari percakapan hingga orang tua yang kulitnya telah keriput seluruhnya itu datang dan duduk di sampingku.
Kombur itu pun dimulai dengan pertanyaan dasar, “Dari mana, Nak?”
Di kota tempat tinggalku terdapat sebuah kebiasaan masyarakat yang konon katanya telah disepakati sebagai sebuah budaya dan harus dilestarikan. Budaya itu Kombur. Jika didefenisikan, kombur itu bercerita. Di kota ini defenisi kombur menjadi lebih spesifik lagi yaitu membicarakan hal-hal secara spontan dan tanpa tujuan khusus. Kombur sering dijadikan oleh orang-orang yang hobi bercerita dengan istilah menjalin kedekatan atau silaturahim.
Kombur yang membicarakan hal-hal kebenaran atau fakta-fakta hanya disebut Kombur saja namun jika sudah dibumbui dengan cerita-cerita bohong dan tak masuk akal akan bertambah nama menjadi Kombur Malotup. Intinya, kombur itu hanya seperti kau bertemu dengan seseorang lalu menceritakan apa saja hingga ternyata kau sadar memiliki banyak kesamaan dengannya atau bahkan mungkin memiliki keterikatan. Yang terakhir terjadi kepadaku.
“SMA Ujung Tanjung, Pak!” jawabku sopan.
“Kalau rumah, dimana?”
“Di jalan Ambacang, Pak.”
“Ambacang yang dekat dengan Sudirman? Kota?”
“Iya, Pak!”
“Ada saudaraku di situ, Jalan Ambacang dimananya?Pak Hasyim kenal, Kau? Orang jalan Ambacang, itu!”
“Pak Hasyim yang tukang kayu ya, Pak?”
“Iya, terkenal dia itu di jalan Ambacang!”
“Kenal, Pak.”
“Rumahmu di sebelah mana rumah Pak Hasyim?”
“Sekitar empat rumah lagi, Pak!”
“Anak siapa kau?”
“Anak Zainal, Pak!”
“Bah, Zainal yang buka kedai?”
“Iya, Pak!”
“Aduh, tak batutur kau jang! Harusnya kau panggil aku Onyang!”
Lalu duduk seorang orang tua lagi di samping orang tua sebelumnya yang langsung disambut dengan tepukan pada pahanya. Orang tua pertama, yang aku bahkan tak tahu namanya mengatakan kepada orang tua kedua bahwa aku adalah anak Zainal dan sama sekali tak batutur kepadanya. Batutur itu, memanggil dengan sebutan yang tepat atas pertalian saudara. Aku pun bingung, apa mungkin dia saudaraku?
“Memang anak muda zaman sekarang ini, tak beradat!” Kalimat itu disampaikan oleh orang tua kedua yang aku bahkan tak mengerti mengapa dia bisa menarik kesimpulan demikian cepat.
“Harusnya, kau panggil aku Onyang. Kakekmu memanggil aku bapak! Ayahmu memanggil aku kakek!”
Aku paham maksudnya sehingga dia tak perlu melakukan penjelasan yang demikian itu. Jadi, si orang tua pertama ini merasa bahwa seharusnya aku memanggil dia Onyang sebab Kakekku memanggil dia Bapak atau di masa sekarang lebih sering diganti menjadi Om. Tapi tunggu dulu, mengapa pula Kakekku memanggil dia Bapak, darimana datangnya? Aku tahu dia akan segera menjelaskan.
“Jadi pasiloroan Orang Rumahku tutur Bapak dari Nenek kau!”
Untunglah aku juara umum di sekolah dan selalu belajar dengan giat sehingga tak sulit bagiku untuk mencerna hubungan keluarga yang sebenarnya sangat jauh itu. Pasiloroan artinya sepupu sedangkan Orang Rumah artinya pasangan. Sebab orang tua yang sedang bercerita ini adalah laki-laki maka Orang Rumahku artinya istirnya. Jadi, hubungan saudara kami adalah seperti ini; Orang tua ini menikah dengan seorang perempuan yang memiliki sepupu. Sepupunya ini merupakan Om dari Nenekku sehingga Nenekku juga harus memanggil istrinya Tante dan memanggil orang tua itu Om. Hal ini pula yang membuat Kakekku juga harus memanggil demikian. Secara otomatis, ayahku harus memanggil dia Kakek dan aku harus memanggil dia Onyang.
Aku menyahuti itu semua dengan hati yang kebas. Dikatakan tak tahu adat hanya karena memanggil orang dengan julukan tak tepat pada pertemuan pertama? Aku ingin protes namun akhirnya kuterima dengan menganggukkan kepala sambil mencoba mencari alasan agar bisa pergi dari circle yang aneh ini. Belum sempat aku menemukan alasan, orang tua pertama memanggil seorang orang tua lain.
“Anak si Zainal ini ternyata!”
“Zainal mana?”
“Zainal jalan Ambacang.”
“Bah, Cucuku lah berarti!”
Jika boleh membela diri, bagaimana mungkin aku bisa mengetahui panggilan untuk semua orang sedang nama sepupu kandung pun aku sering lupa. Lalu, apakah persaudaraan yang seperti itu masih harus diingat sebagai tali persaudaraan? Bukankah jika demikian maka kita semua akan bersaudara sebab jika ditarik tali persaudaraan maka kita semua akan tersimpul pada Nabi Adam yang mula-mula?
Setidaknya, ada dua hal yang membuat aku tidak cocok dengan budaya Kombur untuk mencari tali persaudaraan itu. Pertama, aku adalah orang yang paling sulit mengingat nama orang. Kedua, ayahku tak pernah mengajarkannya. Saat kuceritakan tentang tragedi tak beradat itu kepadanya, ayah hanya tertawa dan berkata, “Aku saja tak kenal, sudaro talian kontutnyo itu!”
Sudaro talian kontut atau saudara tali kentut pertama kali kudengar dari ayah yang artinya saudara yang sangat jauh sekali dan sebenarnya juga bukan saudara namun dihubung-hubungkan agar menjadi saudara. Setelah mendengar kalimat dari ayah dan pengalamanku dibilang tak beradat itu, aku sering memperhatikan orang-orang yang sedang bercerita. Ternyata memang, orang-orang kampungku ini hampir kesemuanya punya hobi demikian. Aku sering melihat dua orang yang baru bertemu akhirnya mengatakan, “Ah, berarti bersaudaralah kita!”
Ayah memang tidak suka itu semua. Ayah tidak terlalu suka bertamu, pesta, tempat ramai dan tidak suka bercerita. Mamak bahkan sering marah dengan kebiasaan ayah yang dinilai mamak buruk. Saat Idulfitri tiba,ayah tidak pernah mau diajak mengunjungi saudara kecuali mamak sudah mengamuk dan memaksa. Itupun, ayah hanya mau mengunjungi saudara yang benar-benar dekat, bukan saudara yang dihubung-hubungkan atau istilah ayahku sudaro talian kontut tadi. Idulfitri tahun ini, ayah mendapatkan kunjungan dari beberapa saudara talian kontut yang tak pernah kami duga.
Lebaran tahun ini Pak Samsul tidak hanya datang membawa istri melainkan turut serta satu rombongan lain. Rombongan itu adalah Pak Harun dan istrinya. Pak Harun kukenal sebagai Camat Kecamatan Muara Balai Kiri. Aku yang merupakan anak paling kecil dan menikah dengan orang Muara Balai juga menjadi orang yang menjaga rumah mamak dan ayah selama lebaran sehingga aku turut menyambut semua tamu yang datang. Dua orang abangku mudik ke kampung istrinya masing-masing. Biasanya, setelah lebaran kedua, tamu mamak dan ayah sudah habis dan baru kemudian aku dan istri mengunjungi sanak saudara dari pihak istriku.
Menurut cerita Pak Samsul yang merupakan sepupu kandung ayah, Pak Harun ingin ikut berlebaran sudah direncanakan sejak akhir Ramadan. Pak Samsul yang kebetulan satu masjid dengan Pak Harun bekombur tentang lebaran dan rencana-rencana yang akan dilakukan. Dalam percakapan itu Pak Samsul menceritakan rutinitasnya mengunjungi ayahku. Pak Harun kemudian menyebutkan bahwa sebenarnya dia dan ayahku saling kenal dan terdapat tutur saudara. Pak Harun menjelaskan pertalian saudara dirinya dengan ayahku yang disambut dengan ekspresi penuh kebohongan oleh ayah. Ayah mengerti tentang pertalian yang disebutkannya, tapi apakah pertalian sejauh itu bisa dikatakan saudara?
Hari ketiga lebaran aku urung berpergian ke rumah saudara dari keluarga istriku sebab tamu lain datang ke rumah mamak dan ayah. Dua rombongan itu datang hanya berjarak sekitar lima belas menit. Kedua orang ini memang dikenal oleh ayahku dan lagi-lagi ayah mengangguk ketika keduanya mengaku bersaudara dengan ayah. Aku mendengarkan penjelasan dari keduanya yang sangat asyik menghubungkan tali persaudaraan itu dan mengangguk, bisa juga sih itu dikatakan saudara, tak kontut-kontut kali.
Tamu yang pertama datang adalah Pak Abdi, beliau adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan. Tamu kedua adalah Pak Afrizal yang merupakan Kepala bagian Organiasi dan Tata Kelola Perangkat Daerah. Mereka menghabiskan waktu satu jam di rumah ayah dan datang membawa berbagai buah tangan. Kami cukup heran tapi memang masih tak menduga penyebab datangnya sudaro talian kontut ini.
Setelah libur lebaran, aku baru mengerti mengapa mereka datang kerumah ayah. Ternyata, yang menjadi target mereka sebenarnya adalah aku. Hal ini kudapati ketika ketiganya menghubungiku dan mengajak bertemu lantas membawa-bahas nama saudara untuk meminta bantuanku menjaga jabatan mereka dengan wali kota yang baru terpilih.
Pemilihan wali kota telah selesai pada November tahun lalu. Wali kota pun telah dilantik pada Februari tahun ini. Wali kota yang semula dinilai akan kalah ini hanya didukung oleh satu persen PNS sebab peluang Petahana memenangkan kontestasi sangatlah besar. Hanya selisih tujuh ribuan suara antara petahana yang didukung oleh 99% PNS dengan pemenang, wali kota baru.
Dari satu persen itu, aku termasuk salah satunya. Aku bahkan bukan sekadar pendukung melainkan salah satu orang terdekat wali kota baru. Aku bahkan sampai dicopot dari jabatan sebagai lurah sebab ketahuan tidak mendukung petahana. Saat itu, sekitar enam bulan setelah dilantik menjadi lurah, aku dipanggil oleh petahana. Dia memintaku untuk mendukung pencalonannya untuk periode kedua. Aku, secara terbuka, mengatakan tidak bersedia.
“Mohon maaf Pak Wali. Tanpa mengurangi rasa hormat! Ini bukan tentang siapa paling baik atau siapa paling buruk, atau tentang siapa paling berprestasi atau tidak berprestasi. Menurut saya, pemilihan wali kota itu hanya tentang siapa dekat dengan siapa. Sebenarnya, saya bisa saja mengatakan iya kepada Pak Wali hari ini dan menunjukkan jati diri saya yang sebenarnya di bilik suara nanti, tapi untuk apa kita hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan seperti itu?”
Aku kemudian menjelaskan kepada petahana bahwa kedekatanku dengan salah satu calon lain sudah dimulai sejak aku masih kuliah. Calon wali kota yang sempat menetap lama di kota provinsi pernah mencari guru les untuk anaknya dan setelah dihubungkan oleh berbagai teman, aku terpilih menjadi guru les anaknya itu. Sejak mengajar les anaknya itu aku cukup dekat dengan keluarga mereka hingga hari ini. Bahkan saat calon wali kota ini pulang kampung dan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi, aku adalah tim suksesnya meskipun tidak tercatat sebab aku adalah seorang PNS. Kami selalu duduk meminum kopi, diskusi dan bahkan sesekali sering berolahraga bersama.
Aku menutup penjelasanku itu dengan kalimat tegas, “Saya tidak bisa memilih Pak Wali pada pemilihan kali ini karena salah satu orang terdekat saya juga mencalon untuk jabatan yang bapak inginkan.”
Dua minggu setelah pertemuan itu aku diturunkan dari jabatan dan cerita tentang hal itu langsung menyebar entah oleh siapa. Saat itu calon wali kota yang akan kudukung mengunjungiku dan kami berfoto bersama. Dalam caption yang diunggahnya di akun media sosial, calon wali kota itu menulis: Sabar ya Pak Lurah. Nanti kita kembalikan!
Sudaro talian kontut ini semakin terlihat ketika aku masuk rumah sakit sebab diare. Entah siapa yang memulai dan entah bagaimana kabar bisa beredar, beberapa pejabat datang mengunjungiku. Mereka datang membawa berbagai buah tangan dan menceritakan silsilah pertalian saudara kami. Sejak kejadian Pak Harun, Pak Abdi, dan Pak Afrizal, aku sudah tahu apa yang diinginkan mereka dan sama sekali tak lagi peduli pada silsilah pertalian persaudaraan yang dijabarkan mereka.
Wali kota baru datang di hari kedua aku dirawat. Saat itu ada tiga orang PNS dari Dinas Pendidikan yang datang menjengukku, termasuk Pak Abdi. Pak Abdi datang atas nama saudara dan dua orang lagi mengaku menemani Pak Abdi. Mungkin mereka tidak punya talian kontut yang bisa dihubung-hubungkan denganku. Ketiga orang itu duduk bersama wali kota baru. Wali kota baru yang datang tanpa buah tangan apapun tak sudah-sudah mengejekku yang masuk rumah sakit karena diare.
“Tak keren kali sakit kau Sulaiman, masuk rumah sakit karena diare, mencret!” ucapnya yang disambut dengan tawa keras oleh para pejabat itu yang terasa sumbang dan tak tulus di telingaku.
Sebelum Wali kota baru pulang dia bertanya secara terang-terangan kepadaku. “Kau ingin jabatan apa?”
“Terserah Pak Wali. Aku tidak dikasi jabatan pun akan tetap di barisan Pak Wali!”
“Ada orang yang mau kau selamatkan dan kita kasih jabatan?” Tanyanya sekali lagi.
“Tak ada Pak Wali, satupun tidak!” jawabku tegas.
*) Image by istockphoto.com


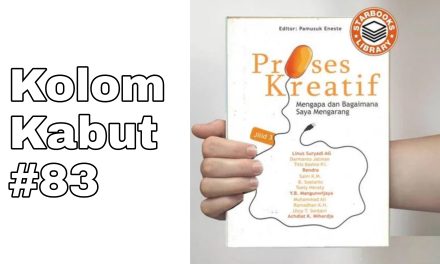
















plot twist nya diluar dugaan