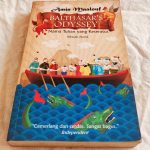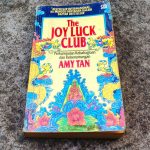KURUNGBUKA.com – Jika saya harus memilih kata-kata yang paling tidak saya sukai dalam bahasa Indonesia, kata yang akan berada pada daftar teratas pasti deforestasi. Bukan, bukan karena ia antek serapan asing, tetapi karena kata ini sungguh menyembunyikan perusakan alam dengan terang-terangan.
Barangkali, bahasa Indonesia tidak bermaksud sejauh itu. Ia hanya menyerap dari bahasa Inggris Abad Pertengahan, deforestation, yang menyerap awalan de- dari bahasa Latin. Awalan ini multifungsi: ia membalikkan, menghilangkan, mengurangi, dan menurunkan makna kata dasar yang dilekatinya. Ambil contoh, deaktivasi, degradasi, dekadensi, devaluasi, detoksifikasi, desentralisasi demobilisasi, demiliterisasi, dekonstruksi, dekolonisasi.
Dalam bahasa Inggris, kata deforestation teridentifikasi digunakan pertama kali pada tahun 1874 (Lihat Kamus Merriam-Webster Daring). Forestāre dalam bahasa Latin berarti “menanam pohon.” Jika diartikan secara harfiah, deforestation berarti “menghapus pohon dari suatu wilayah.”
Sebelum deforestasi merebak penggunaannya, ada istilah assart pada abad ke-16 untuk menyebut aktivitas pembukaan lahan, meski pada akhirnya, istilah tersebut gagal bersaing karena dianggap hanya menggambarkan tindakan dalam skala kecil.
Praktik deforestasi telah ada saat manusia mulai membuka lahan pertanian pada abad 10.000 SM. Menurut laman climatetransform.com, saat ini, pertanian masih menjadi penyebab utama deforestasi bahkan aktivitas pertanian bertanggung jawab atas setidaknya 80 persen deforestasi di daerah tropis, sisanya disebabkan oleh pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan permukiman juga berkontribusi.
Bahasa Indonesia memiliki variasi istilah untuk deforestasi: pembalakan hutan, penggundulan hutan, Kedua istilah itu menyakitkan tapi lebih jujur mengungkap kerakusan pemerintah manusia untuk membuka sebanyak-banyaknya lahan untuk kepentingan industri yang gila-gilaan. Video gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatra Utara yang viral di media sosial dalam 5 hari terakhir membuka mata kita sekaligus membongkar aktivitas perusakan lahan besar-besaran yang selama ini terjadi dan jauh dari sorot media.
Sebenarnya, kita tidak akan bereaksi dan curiga lebih jauh jika saja potongan pernyataan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan soal gelondongan kayu (besar-besar dan terpotong rapi banget loh itu) adalah pohon lapuk dan tumbang alami, tidak beredar luas di media sosial.
Ditjen Gakkumhut (singkatan ini pun merepotkan lidah) sebenarnya punya tugas mulia. Ia lembaga di bawah Kementerian Kehutanan yang bertugas menegakkan hukum untuk menjaga kelestarian hutan. Fungsi utama lembaga ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum, pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan.
Akan tetapi, kita telah kenyang dengan cara sebagian besar pejabat kita merespons kritik dengan bahasa-bahasa yang manipulatif, susah dikunyah, sekaligus mengintimidasi tingkat kecerdasan semacam itu. Kejadian-kejadian viral yang menuai kritik keras di media sosial (bahkan memicu aksi berdarah dan perusakan fasilitas umum pada akhir Agustus lalu) tidak pernah membuat mereka jera ngomong asal-asalan di depan kamera jurnalis dan wartawan, apalagi berkaca pada kemampuan wicara publik (public speaking) yang dimiliki. Saya curiga, sebagain besar orang yang dipercaya menduduki jabatan strategis di negeri ini belum belajar teori komunikasi politik atau mungkin lupa bahwa pesan yang disampaikan oleh seseorang yang punya jabatan memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini publik, membentuk persepsi, dan bahkan menggerakkan gerakan kolektif warga.
Mari simak pernyataan serupa dari Pak Ditjen Gakkkumhut di laman liputan6.com:
“Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan.”
Bahasa manipulatif, penuh istilah dan akronim teknis, tidak gramatikal dan tidak logis dan meremehkan kemanusiaan semacam itu banyak berceceran di kutipan-kutipan berita juga potongan video yang kita temukan di beranda media sosial. Sering kali, pernyataan-pernyataan itu buru-buru diralat dengan maaf atau mengungkap maksud mereka sebenarnya.
Dalam sastra, deforestasi bisa lebih mencekam. Dalam artikelnya di Jurnal European Romantic Review, Volume 26 tahun 2015, Broken Arbour: “The Ruined Cottage” and Deforestation, Matthew Rowney menelusuri puisi William Wordsworth the Ruinned Cottagge dan mengaitkannya dengan sejarah deforestasi dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Broken Arbour adalah simbol dari kehancuran ekologis akibat deforestasi panjang di Inggris. Rowney menelusuri bagaimana penebangan hutan besar-besaran terjadi sejak masa Tudor hingga periode Romantik, didorong oleh kolonialisme, industri besi, tembaga, dan pembangunan kapal. Di Indonesia, cerpen-cerpen Korrie Layun Rampan juga mendedah soal serupa, dalam konteks kehancuran alam akibat eksploitasi hutan yang ia lihat langsung dari apa yang menimpa hutan-hutan di pedalaman Kalimantan.
Satu hal yang menarik, istilah deforestasi juga digunakan oleh Philip Wadler dalam ranah ilmu komputer pada tahun 1990. Ia menggunakan deforestation dalam makalahnya, Deforestation: Transforming Programs to Eliminate Trees(terbit di Jurnal Theoretical Computer Science, Volume 73, Nomor 2, hal 231—248, edisi Juni 1990, untuk menjelaskan sebuah teknik optimisasi bernama algoritma deforestation. Istilah ini disebut sebagai teknik yang mampu “menebang” struktur data perantara, sehingga program menjadi lebih efisien, hemat memori dan lebih cepat.
Wadler menunjukkan bagaimana deforestasi menjadi metafora yang cerdas. Namun, banjir Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat lagi-lagi memberi tahu, istilah ini tak lebih dari kedok yang berupaya memberi tahu kenyataan pahit mengenai semakin hilangnya hutan kita, juga ancaman yang menanti kita ketika hujan turun lagi. Hujan pun tak lagi romantis seperti dalam lagu Ratih Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Kita tak bisa lagi sekadar berlindung dari payung hitam agar tidak basah. Kita kini harus berlindung dari jargon teknis dan pernyataan-pernyataan blunder pejabat kita, agar kesehatan mental kita tetap terjaga.
*) Image by ANTARA FOTO/Yudi Manar
Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<