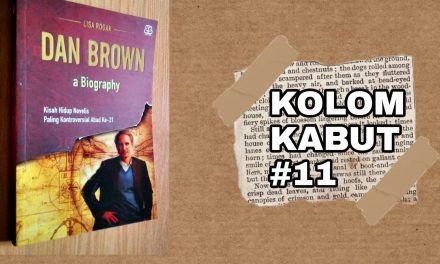Aku menemukannya di trotoar, duduk dengan kepala tertunduk, tangannya gemetar memegang paku panjang yang ujungnya sudah menempel di keningnya. Di sebelahnya, ada palu kecil berkarat. Aku tidak tahu sudah berapa lama ia di sana, tapi orang-orang melewatinya begitu saja, seperti patung di tengah kota yang terlalu biasa untuk dilihat dua kali.
“Hari buruk?” tanyaku, jongkok di depannya.
Lelaki itu mendongak, menatapku dengan mata sayu yang separuhnya merah seperti seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak tidur, atau terlalu banyak hidup. “Setiap hari buruk. Aku cuma ingin memastikan aku masih merasa sesuatu.”
“Dengan memaku kepalamu sendiri?”
Ia mengangkat bahu, seperti itu hal yang paling masuk akal di dunia. “Nyeri itu nyata.”
Aku menatapnya lama, lalu merogoh saku jaketku. Aku menawarkan sebatang rokok yang kuselipkan di antara bibirnya, menyalakannya dengan korek gas yang suaranya kecil tapi nyaring dalam hening.
“Siapa namamu?” tanyaku.
“Nade.”
“Nama yang bagus.”
“Bukan. Itu cuma suku kata dari nada. Mungkin ibuku berharap aku bisa menjadi harmoni dalam hidupnya. Nyatanya, aku cuma distorsi.”
Aku mengembuskan asap ke udara. Di seberang jalan, layar LED raksasa menampilkan iklan kripto terbaru yang menjanjikan kebebasan finansial dalam lima langkah sederhana. Di belakangnya, ada spanduk kampanye dengan wajah seorang pria yang mengangkat tangan dengan senyum buaya. Di bawahnya ada slogan Rakyat Sejahtera, Negara Kuat, yang baru saja diserang oleh grafiti merah bertuliskan Makan Saja Kami Sulit, Anjing.
Aku kembali menatap Nade, lelaki yang sedang mencoba menjadi papan kayu untuk paku yang ia genggam.
“Kenapa kau berhenti?” tanyaku.
Ia tertawa pelan, sesuatu yang lebih mirip desisan dari seseorang yang kehabisan tenaga untuk benar-benar menikmati humor hidup. “Karena aku takut.”
“Takut mati?”
“Takut kalau aku bahkan tidak bisa merasakan sakitnya.”
Aku memandang matanya. Ada kehampaan di sana, seperti rumah tua yang ditinggalkan pemiliknya. “Kau ingin ikut denganku?” tanyaku akhirnya.
Ia mengangkat alis. “Ke mana?”
“Ke tempat di mana kita bisa mabuk tanpa takut dihakimi. Ke tempat di mana dunia ini cuma latar belakang yang tak perlu terlalu kita pikirkan.”
Nade terdiam sesaat, lalu ia mengambil palu kecilnya, memasukkannya ke dalam saku jaket, dan berdiri.
“Ayo!”
Tempat itu bernama Terminal Senja. Sebuah bar kecil yang tersembunyi di antara lorong-lorong kumuh yang hampir tak bisa dibedakan dari reruntuhan. Di dalamnya, orang-orang duduk dalam kebisuan, beberapa hanya menatap gelas mereka, beberapa berbicara dengan diri sendiri.
Di sudut ruangan, seorang lelaki tua dengan janggut seputih kertas sedang menggambar sesuatu di atas serbet, sementara seorang pelayan dengan mata cekung seperti lembah kematian menuangkan bir murahan ke dalam gelasnya.
Aku dan Nade duduk di bar. Aku memesan gin murah, sementara Nade hanya menatap pantulan dirinya di cermin di belakang bartender.
“Kenapa tempat ini terasa seperti rumah?” tanyanya pelan.
“Karena di sini tidak ada yang peduli siapa kau sebelumnya.”
Ia mengangguk kecil, lalu berkata, “Kau belum memberitahuku siapa namamu.”
“Orang-orang di sini biasa memanggilku Kabel.”
Ia tertawa kecil. “Seperti kawat?”
“Seperti sesuatu yang kusut dan sulit diurai.”
Ia mengangguk lagi, kali ini dengan pemahaman. “Kau juga rusak, ya?”
Aku mengangkat gelasku. “Semua orang di sini rusak. Dunia tidak membiarkan kita utuh.”
Nade tersenyum miring. “Aku tidak pernah merasa lebih nyaman daripada saat ini. Ironis, ya? Aku bertemu seorang asing di trotoar, lalu beberapa jam kemudian aku merasa seperti menemukan seseorang yang mengerti.”
Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di balik matanya—sesuatu yang aku kenal.
“Karena kita hidup di generasi yang disuruh untuk terus berlari, tapi kita tidak tahu ke mana,” kataku akhirnya.
Nade menarik napas panjang. “Aku dulunya percaya pada sesuatu. Aku percaya bahwa kerja keras akan membawaku ke tempat yang lebih baik. Bahwa jika aku cukup kuat, aku bisa mengubah nasib.”
Aku meneguk gin. “Lalu?”
“Lalu aku sadar bahwa dunia ini adalah mesin besar yang sudah diprogram untuk menelan kita hidup-hidup. Aku kerja hampir sepuluh jam sehari, tapi gaji yang kuterima cuma cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup. Aku menabung selama bertahun-tahun untuk sesuatu yang akhirnya menguap dalam semalam. Aku berusaha jujur, tapi dunia ini tidak punya tempat untuk orang jujur. Aku mencoba menahan diri, tapi dunia ini justru menertawakan orang-orang yang tidak berani menggigit balik.”
Ia mengusap wajahnya. “Jadi, aku berhenti mencoba.”
Aku menatapnya. Aku ingin memberitahunya bahwa aku mengerti. Bahwa aku juga pernah sampai di titik itu, titik di mana satu-satunya pilihan adalah menekan paku ke dahi, hanya untuk memastikan bahwa kita masih manusia, bahwa kita masih bisa merasakan sesuatu.Tapi, aku tidak mengatakannya.
Sebagai gantinya, aku mengangkat gelasku. “Untuk kita.”
Nade menatapku, lalu mengangkat gelasnya juga. “Untuk kita yang masih di sini, entah kenapa.”
Kami minum dalam diam.
Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Politik kotor, janji kosong, harga yang naik lebih cepat daripada upah, orang-orang yang makin asing satu sama lain, kematian yang begitu murah seperti barang-barang diskon.
Tapi di sini, di bar kecil bernama Terminal Senja, dua orang asing duduk bersebelahan, berbagi kehancuran yang sama, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak merasa sendirian.
Ketika kami keluar dari bar, angin malam terasa lebih hangat dari biasanya.
Nade menatap langit. “Aku tidak tahu apakah aku akan bertahan hidup sampai tua.”
Aku menyalakan rokokku, lalu menyerahkan satu kepadanya. “Aku juga tidak.”
Ia menyalakannya, mengisapnya pelan, lalu bertanya, “Jika kita tahu bahwa dunia ini tidak akan berubah, lalu kenapa kita tetap di sini?”
Aku mengembuskan asap ke udara, memikirkan jawaban itu.
Lalu aku berkata, “Mungkin karena kita masih menunggu alasan.”
Nade menatapku lama, lalu tersenyum tipis. “Sial. Aku harap aku menemukannya sebelum aku kehabisan paku.”
Aku tidak tertawa. Karena aku tahu, di dunia seperti ini, alasan sering datang terlambat. Dan beberapa dari kita sudah terlalu lelah untuk menunggu.
Malang, 3 Februari 2025
*) Image by istockphoto.com