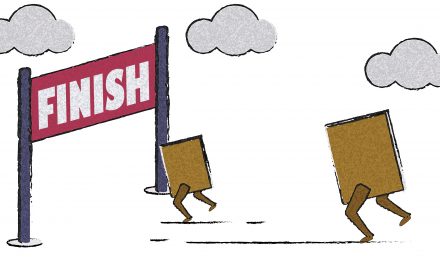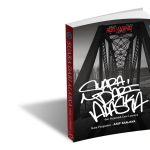Namaku Kiran. Umurku baru genap dua belas tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit yang dulu dikelilingi sawah hijau dan dialiri sungai jernih. Saking jernihnya air sungai itu, warga desaku menyebutnya sebagai sungai kaca. Airnya begitu bening hingga batu-batu dan dasar sungai tampak jelas. Ikan-ikan kecil berwarna perak berenang riang di dalamnya.
Tiga tahun lalu, sebuah pabrik berdiri di hulu. Mula-mula, warga desa senang karena banyak orang yang akhirnya mendapatkan pekerjaan di sana. Tetapi kebahagiaan tersebut cepat pudar. Air sungai yang dulunya sebening kaca perlahan berubah warna menjadi kecokelatan. Bau menyengat menusuk hidung setiap kali angin membawa uapnya. Ikan-ikan mati mengapung, sawah-sawah warga mengering, tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar sungai tampak muram, dan anak-anak desa tak lagi bermain di tepinya.
Hari ini, aku duduk di tepian sungai yang dulunya adalah tempatku dan teman-teman mencari kecebong. Aku membawa buku tulis dan pensil. Aku ingin menulis sebuah surat. Surat ini bukan untuk teman atau guru, tetapi untuk mereka yang membuat sungai kaca sakit.
Aku menulis dengan hati-hati.
Kepada tuan yang tak pernah datang ke sini. Perkenalkan, aku Kiran. Anak yang tumbuh bersama sungai kaca. Aku ingat betul ketika airnya sejuk dan suaranya menenangkan malam. Sungai ini memberi warga desa minum, memberi ikan untuk makan, memberi sawah para warga hidup. Tapi kini, warnanya seperti malam yang kehilangan bintang, baunya pun seperti luka yang tak pernah sembuh.
Ibu tak lagi menjemur pakaian di tepian. Bapak tak lagi turun ke sawah. Lalu aku? Aku tak lagi berani menceburkan kakiku ke dalamnya. Setiap tetes air kini membawa gatal dan perih. Tuan, sungai ini seperti ibu bagi kami. Saat ini ibu kami sedang sekarat.
Jika tuan membaca surat ini, aku mohonpulihkanlah sungai kaca. Bukan untukku saja, tetapi untuk semua anak yang ingin bermain di air tanpa takut sakit. Untuk semua petani yang ingin panennya kembali. Untuk semua burung yang rindu minum di tepian. Kami tak butuh janji panjang. Kami hanya butuh air sungai yang kembali jernih.”
Setelah menulis, aku melipat surat itu. Mungkin surat itu tidak akan sampai ke tangan yang tepat. Tetapi aku percaya, kata-kata punya kaki sendiri untuk berjalan.
Sore itu, aku menemui bapak di beranda. “Pak, bolehkah aku mengirim surat ini ke kantor pabrik di hulu?” tanyaku dengan penuh harap.
Bapak memandangku lama. Matanya terlihat lelah, mungkin karena berbulan-bulan mencoba melawan tanpa hasil yang jelas. Ia tersenyum tipis. “Boleh. Tapi jangan hanya kirim ke mereka. Kirim juga ke kantor desa, ke pemerintah, bahkan ke surat kabar. Biar semua orang tahu.”
Keesokan harinya, aku mengayuh sepeda ke kantor pos. Di perjalanan, aku melewati tanah kosong yang dulunya sawah. Anak-anak desa bermain layang-layang di sana. Dari kejauhan, asap dari cerobong pabrik membubung, menodai langit sore.
Seminggu berlalu. Tidak ada balasan. Tapi setelah aku mengirim surat itu, sesuatu terjadi. Wartawan datang ke desaku. Mereka mewawancarai bapak, ibu, serta beberapa warga desa. Mereka juga memotret sungai yang menghitam.
Aku tidak tahu apakah suratku yang membawa mereka atau kabar dari orang lain. Satu hal yang aku tahu, sejak berita itu tayang, orang-orang mulai bicara. Beragam reaksi bermunculan. Ada yang marah, protes, ada juga yang iba.
Namun, pabrik itu tetap membuang limbah. Sungai kaca tetap hitam dan bau busuknya semakin menusuk indra penciuman. Malam itu, rapat desa diadakan oleh pak kades. Balai desa dipenuhi oleh warga. Kepala desa berdiri di depan mencoba menenangkan suasana.
“Kita sudah mengirim protes resmi,” katanya, “tapi mereka bilang limbahnya aman.”
“Aman?” teriak Pak Rahmat, salah satu petani yang sawahnya kini tandus. “Aman bagaimana? Kalau aman, kenapa anak saya gatal-gatal setiap mandi?”
Suasana ricuh. Aku duduk di pojok, menggenggam surat balasan yang belum pernah aku terima. Aku ingin bicara, tapi suaraku terasa kecil di tengah teriakan para warga. Hingga tiba-tiba, Pak Rahmat menunjuk ke arahku, “Anak ini yang kirim surat, kan? Ceritakan lagi, biar mereka dengar dari yang merasakan!”
Semua mata memandangku. Kakiku gemetar, tapi aku tetap maju. “Aku cuma mau bilang kalau sungai kaca itu tidak hanya milik kita saja, tetapi juga milik ikan, burung, tumbuhan di sekitarnya, dan tanah. Kalau kita biarkan mati, kita juga perlahan-lahan akan ikut mati,” ujarku dengan lantang.
Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan terdengar. Tidak lama kemudian, keputusan pun diambil. Warga desa akan menggelar aksi di depan pabrik. Aksi itu dilakukan seminggu kemudian. Warga membawa poster, spanduk, serta foto-foto sungai kaca sebelum dan sesudah tercemar limbah. Aku berdiri di barisan depan bersama bapak.
Manajer pabrik keluar mengenakan kemeja rapi. “Kami akan evaluasi,” katanya singkat. Janji yang terdengar seperti angin lewat.
Bulan berikutnya, truk-truk limbah masih datang. Tapi kini, setiap kali mereka lewat, ada mata yang mengawasi. Warga desa tidak lagi diam. Beberapa aktivis lingkungan mulai membantu mengajukan tuntutan. Aku tahu ini belum berakhir. Sungai kaca masih menghitam, tetapi setidaknya warga kini tidak sendirian.
Malam itu, aku kembali menulis.
“Sungai kaca, aku berjanji tidak akan berhenti. Surat-suratku akan terus berjalan. Sampai suatu hari nanti aku dan semua orang bisa becermin lagi di permukaanmu, ikan-ikan kecil akan kembali menari di dalammu, tanaman liar tidak akan muram lagi di tepianmu, gerombolan burung akan kembali menyeruput airmu, dan sawah para warga akan kembali merasakan sejuknya aliran airmu.”
Aku menutup buku tulis dan menatap ke arah sungai. Bulan memang masih tertutup awan, tapi aku tahu ia tetap ada. Sama seperti harapanku. Mungkin tertutup kabut untuk sementara waktu, tapi harapan itu tidak pernah padam.
***
Setahun setelah surat pertamaku dikirim, sungai kaca belum sepenuhnya pulih. Namun, warnanya tidak lagi sepekat dulu. Beberapa bagian mulai memperlihatkan aliran cokelat muda, pertanda bahwa ia sedang berjuang. Kabar tentang perjuangan desaku tersebar. Mahasiswa dari kota datang membawa spanduk dan kamera. Komunitas pencinta lingkungan mengajak warga menanam pohon di bantaran sungai. Bahkan, ada sekolah yang mengirim murid-muridnya untuk belajar tentang pentingnya menjaga air supaya tetap bersih.
Suatu sore, aku menerima sebuah paket. Di dalamnya ada selembar kaus bertuliskan #HidupkanSungaiKita dan sepucuk surat singkat.
“Kiran, suratmu membuat kami bergerak. Teruslah menulis. Air mengalir karena ia tak pernah menyerah mencari jalannya.”
Aku memeluk kaus itu erat-erat. Sungai kaca mungkin belum kembali jernih, tapi ia kini punya banyak anak yang siap menjaganya. Aku tahu, setiap surat yang kutulis tidak hanya untuk sungai ini, tetapi juga untuk semua sungai yang mulai menghitam di negeri ini.
*) Image by istockphoto.com