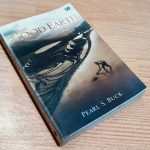KURUNGBUKA.com – Bahasa Indonesia, dan para penuturnya, tetap (akan) mengejutkan, membahagiakan, menggugupkan, dan memerangahkan saya. Kalimat Andre Möller dalam bagian penyudahan di buku Untung Gundul (Penerbit Buku Kompas, 2022) membuat hati saya menghangat. Bagi penulis berkebangsaan Swedia itu, bahasa Indonesia barangkali merupakan bahasa ketiganya. Namun, saya mampu membaca ketakjubannya dengan jelas terhadap bahasa yang baru-baru dipakai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, pada Selasa, 4 November 2025.
Ya, Andre Möller memang pernah tinggal cukup lama di Indonesia, pernah menjadi mahasiswa di Indonesia dan barangkali sudah telanjur kepincut pada masakan-masakan Indonesia. Barangkali itu bukan alasan-alasan yang bisa diperdebatkan mengapa ia justru lebih fasih berbahasa Indonesia ketimbang kita yang menjadikan bahasa Indonesia sekadar alat komunikasi yang bisa dipakai saat perlu.
Hari-hari ini, bahasa asing hampir mendominasi keseharian kita. Bahasa Indonesia minder ketika bahasa Korea tampak mampu mendekatkan diri penuturnya secara psikologis terhadap Kim Soo Hyun atau Ji Chang Wook atau bagaimana bahasa Inggris berhasil membuat kita merasa lebih cerdas; atau bagaimana bahasa Arab membuat kita merasa lebih alim; atau bagaimana bahasa Mandarin kini lebih mampu memastikan cerah atau tidaknya masa depan kita. Anda dapat menyebut alasan lain mengapa bahasa asing tampaknya lebih menantang diseriusi daripada bahasa Indonesia.
Sampai hari ini, bahasa Indonesia statusnya cukup menjadi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di jurusan-jurusan nonbahasa Indonesia di perguruan tinggi, sehingga tidak mengherankan apabila kemampuan menulis karya ilmiah kita pas-pasan (cenderung memalukan). Kompetensi berbahasa Indonesia toh tidak terlalu penting karena selalu ada mesin pencari yang bisa kita andalkan, ditambah lagi kehadiran ChatGPT dan aplikasi parafrasa yang begitu mudah diakses. Jangankan menulis karya ilmiah, membuat kalimat pun harus mengandalkan Google. Kejadian ini saya alami pada suatu waktu, di awal pertemuan perkuliahan MKDU Bahasa Indonesia saat menjadi salah satu dosen tamu di sebuah kampus, saya meminta mahasiswa satu membuat kalimat sederhana. 10 menit kemudian, ketika mereka mengumpulkan kalimat-kalimat itu, saya mendapati jawaban yang hampir seragam. Saya pun mencari tahu siapa yang menyontek dan siapa yang memberi sontekan. Jawaban mereka membuat saya tercengang, “Dari Google, Bu.” Ada tiga pertanyaan yang muncul di kepala saya hari itu: Setergantung itukah mereka pada mesin pencari? Separah itukah kemampuan berbahasa Indonesia mereka? Atau jangan-jangan mereka hanya enggan berpikir?
Kita juga menyaksikan sebagian besar pejabat kita gagal menunjukkan keteladanan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun (juga logis) di ruang publik. Badan Bahasa seolah berjuang sendiri dalam mengangkat muruah bahasa Indonesia, sertifikat TOEFL lebih wajib dimiliki daripada sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di setiap seleksi masuk pascasarjana di perguruan-perguruan tinggi dalam negeri.
Pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini adalah reaksi saya ketika menyimak komentar-komentar warganet pada unggahan-unggahan terkait dengan ulasan buku Gratis Ongkir: Kelindan dan Sengakrut Bahasa (GPU, 2025). Buku kumpulan esai kebahasaan yang saya tulis dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 tersebut menimbulkan beragam reaksi dan juga pendapat mengenai bahasa Indonesia. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama mengganggu ketika saya menyimak siniar Indah Gunawan dan Cinta Laura Kehl tentang bahasa Indonesia yang miskin kosakata, yang viral akhir Maret 2024 itu.
Kita tahu, Indah dan Cinta berdua tumbuh dalam lingkungan yang sangat terpapar bahasa Inggris sebagaimana yang terjadi pada anak-anak muda di kota-kota besar. Wajar jika keduanya lebih merasa nyaman berbahasa Inggris: berpikir dan becakap-cakap dalam bahasa yang bisa dikatakan menjadi bahasa pertama mereka. Wajar jika kemudian mereka terbata-bata dalam mengekspresikan “pikiran kritis” mereka dalam bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia yang mereka kuasai belum sebanyak kosakata bahasa Inggris mereka. Saat seeorang tumbuh dalam lingkungan yang didominasi oleh bahasa Inggris, kesempatan untuk meningkatkan kompetensi komunikatif dalam berbahasa Indonesia akan berkurang. Keterlibatan seseorang secara aktif dalam lingkungan yang memungkinkan mereka berlatih dan menggunakan bahasa Indonesia secara teratur, termasuk membaca buku, atau artikel dan mendengarkan media berbahasa Indonesia akan sangat membantu mempertajam kompetensi komunikatif tersebut.
Tarigan (2009) mengungkap empat komponen yang tercakup dalam kompetensi komunikatif bahasa, yaitu: 1) kompetensi gramatikal; 2) kompetensi sosiolinguistik; 3) kompetensi wacana, dan 4) kompetensi strategik. Kompetensi gramatikal berkaitan erat dengan penguasaan ciri-ciri dan kaidah bahasa seperti kosakata, pembentukan kata, pembentukan kalimat, ucapan, ejaan, dan semantik linguistik. Kompetensi sosiolinguistik berkaitan dengan ekspresi dan pemahaman makna-makna sosial secara tepat. Secara sederhana dapat dikatakan dengan bagaimana kita memahami penggunakan klitika ki’ dan ko’ dalam dialek Melayu Makassar atau ngana dan ngoni dalam dialek Melayu Manado, misalnya. Atau bagaimana satu kata dalam bahasa tertentu memiliki makna berbeda dalam bahasa lain (contoh beda arti kata fighting dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris). Sementara itu, kompetensi wacana meliputi penguasaan tertulis beragam genre seperti narasi lisan atau tulis, esai argumentatif, menulis surat bisnis, atau laporan ilmiah. Lalu, kompetensi strategik meliputi penguasaan strategi verbal dan nonverbal karena dua alasan: 1) mengimbangi kemacetan-kemacetan dalam komunikasi karena keterbatasan kosakata atau tata bahasa, misalnya, dan 2) meningkatkan keefektifan komunikasi. Bisa jadi apa yang disebut Indah dan Cinta sebagai “menjelaskan dengan bertele-tele atau berbelit-belit” sebenarnya adalah persoalan kompetensi komunikatif bahasa Indonesia mereka yang belum memadai sehingga upaya parafrasa menjelaskan kata mindfulness dan nuance ke dalam bahasa yang tidak terlalu mereka akrabi itu akhirnya gagal.
Belajar bahasa apa pun di dunia, memakai formula yang sama jika kita ingin fasih berkomunikasi, berpikir, membaca dan menulis dalam bahasa itu: kebiasaan. Bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Pertanyaan ini dibuktikan oleh penelitian Tanir (2023) berjudul Beyond known and unknown: Is language learning a set of habits? dan banyak peneliti psikologi sebelumya, baik dalam mempelajari atau memperoleh bahasa secara alami. Ketika kebiasaan itu hilang, seketika kita akan tersendat-sendat, gagap dan kembali berbicara seperti anak-anak yang baru belajar berbicara. Ini biasanya dialami oleh mereka yang terlalu lama merantau dan tidak lagi terlibat dalam beragam tindak tutur dalam bahasa ibunya.
Anak-anak Indonesia yang dari kecil terbiasa menonton Upin-Ipin (bahkan sebelum mereka bisa berbicara) pasti akan fasih berbahasa Malaysia. Demikin pula anak-anak yang sejak kecil terbiasa menoton Pocoyo, Bluey, dan Peppa Pig akan fasih berbahasa Inggris dengan aksen yang sama persis. Anak-anak yang sehari-harinya mendengar bahasa daerahnya, akan fasih berbicara dalam bahasa daerah itu.
Dalam kasus pemerolehan bahasa, kompetensi komunikatif pada tahap ini belum tampak benar, kecuali pada tingkat penguasaan kosakata serta cara melafalkannya. Namun, ketika di luar tontonan tersebut anak-anak itu lagi-lagi mendapati orang-orang di sekitar menggunakan bahasa yang sama, dan mereka juga akhirnya bersekolah di lembaga-lembaga internasional dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, semakin hilanglah kesempatan untuk mengenali bahasa Indonesia, yang akan mempersulit mereka ketika harus berkomunikasi lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia. Pada akhirnya, lingkungan bahasa seperti itu akan menjerumuskan mereka ke dalam persepsi bahwa bahasa Indonesia tidak cukup memadai untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat mereka, oleh karena itu pantas disebut miskin kosakatanya.
Seberapa perlu menguasai bahasa Indonesia? Pertanyaan itu akan terasa urgen saat menghadapi situasi formal: presentasi tugas atau makalah, sidang skripsi, wawancara kerja dan situasi lain yang menuntut hadirnya bahasa Indonesia baku. Sayangnya, kata baku telanjur mendapat konotasi negatif sebagai sesuatu yang kaku. Kita juga dari dulu dicecoki dogma “berbahasa Indonesia yang baik dan benar” tanpa diberi penjelasan bahwa itu berarti menggunakan bahasa Indonesia sesuai situasi dan konteks. Kita tidak mungkin memakai bahasa kamus di mana-mana, kan?
Saya tiba-tiba ingin Andre Möller diundang ke The Indah G Show.
*) Image by zenius.net
Dukung Kurungbuka.com untuk terus menayangkan karya-karya penulis terbaik dari Indonesia. Khusus di kolom ini, dukunganmu sepenuhnya akan diberikan kepada penulisnya. >>> KLIK DI SINI <<<