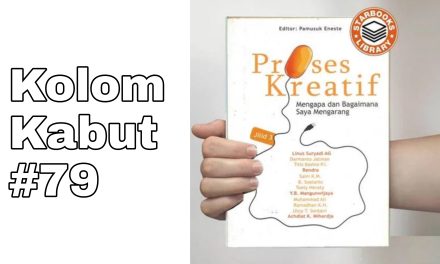Di kampung kami yang jauh dari jangkauan menara-menara tinggi dan sinyal kuat, ada satu kebiasaan turun-temurun yang dijaga dengan khidmat: setiap malam, selepas Isya, warga meletakkan sepiring nasi di depan rumah mereka. Tak perlu lauk. Kadang hanya nasi putih. Kalau ada lebih, diberi garam atau kelapa parut. Nasi itu, katanya, untuk Tuhan.
“Kalau ingin rezeki lancar, jangan lupa beri makan Tuhan,” kata Mak, sambil mengaduk nasi dalam dandang. “Tuhan itu suka yang ingat sama-Nya, meski cuma dengan nasi sepiring.”
Aku tujuh tahun saat pertama kali bertanya, “Emang Tuhan lapar, Mak?”
Mak menoleh cepat dan mencubit kecil lenganku. “Mulutmu jangan lancang. Nanti bisul lidahmu.”
Aku diam, tapi malam itu pertanyaan itu tertinggal di kepalaku. Tuhan itu Maha Kaya, kan? Tapi kenapa masih perlu diberi makan?
Rasa ingin tahuku tak bisa dipadamkan. Malam itu, saat Mak sudah masuk kamar, aku diam-diam duduk di balik jendela, mengintip piring nasi yang baru saja diletakkan di depan pohon jambu. Suasana sunyi. Hanya suara serangga dan tiupan angin pelan yang menemani.
Tak lama kemudian, kulihat seseorang mendekat. Langkahnya pelan, tubuhnya membungkuk. Dari balik kegelapan, muncul sosok lelaki tua berpakaian lusuh, rambut panjang tergerai, dan wajah yang hampir tak terlihat. Ia mendekati piring itu, duduk jongkok, lalu mulai menyuap nasi dengan tangan gemetar.Aku menahan napas. Dia makan perlahan, seolah setiap butir nasi adalah emas. Setelah piring itu bersih, ia pergi seperti bayangan, hilang dalam gelap.
Besok pagi, saat Mak hendak mengangkat piring itu, dia hanya berkata, “Alhamdulillah, habis dimakan Tuhan.”
Aku tak berkata apa-apa.
Beberapa malam setelah itu, aku kembali mengintip. Kali ini ada seorang perempuan tua. Lain waktu, seorang anak lelaki berpakaian robek. Kadang mereka datang sendiri, kadang bergantian. Mereka semua diam, makan dengan ragu, lalu pergi tanpa jejak. Tak ada yang berkata-kata. Tak ada doa. Hanya lapar yang sunyi.
Aku coba bertanya pada Mak, “Siapa saja yang biasa keluyuran malam-malam di kampung ini?”
Mak mengangkat bahu, “Paling si Warto, orang gila yang tinggal di bawah jembatan. Atau itu anak jalanan yang suka ganggu di pasar. Tapi jangan pedulikan mereka. Yang penting, nasi itu buat Tuhan. Bukan urusan kita siapa yang ambil.”
Ucapan Mak terasa seperti pintu yang ditutup dari dalam. Tidak semua orang ingin tahu siapa sebenarnya yang duduk lapar di depan rumah mereka.
Tahun-tahun berlalu. Aku tumbuh dengan rasa bingung yang berubah jadi pengertian. Tradisi tetap berjalan. Setiap malam, piring-piring nasi tetap muncul di pinggir rumah-rumah warga. Tapi tak ada seorang pun yang benar-benar bertanya ke mana nasi itu pergi. Mungkin karena mereka takutjika jawabannya bukan Tuhan.
Di sekolah, kami diajari bahwa Tuhan tidak membutuhkan apa pun. Dia Maha Cukup. Tapi di rumah, kami masih menanak nasi lebih setiap malam, “untuk Tuhan”.Aku pernah mencoba bertanya pada Pak Ustaz di surau. “Kalau nasi itu dimakan orang kelaparan, apa masih boleh disebut untuk Tuhan?”
Pak Ustaz menatapku lama, lalu tersenyum. “Kalau kau memberi makan orang kelaparan karena Allah, berarti kau sudah beri makan Tuhan. Bukankah begitu yang diajarkan Nabi?”
Aku mengangguk pelan. Tapi kenapa orang-orang di kampung tidak pernah bicara soal itu?
Ketika aku SMP, satu per satu tetangga mulai berhenti menaruh nasi malam. “Sekarang sudah modern,” kata mereka. “Tuhan bisa dikasih transfer, bukan nasi.”Kata “Tuhan” kini ada di layar ponsel. Dalam pesan dakwah. Dalam tautan donasi. Dalam status Facebook.Mak juga berhenti. Bukan karena ikut tren, tapi karena beras makin mahal. “Kita saja sudah pas-pasan, Le. Tuhan pasti mengerti.”
Tapi aku merasa ada yang hilang. Sunyi yang dulu ada di malam kampung kami berubah menjadi kosong. Tidak ada lagi langkah pelan mendekati pohon jambu. Tidak ada lagi bunyi sendok kayu di pinggir piring seng.
Kadang aku berpikir, barangkali bukan nasi yang mereka rindukan. Tapi perasaan bahwa masih ada yang peduli. Bahwa dunia belum sepenuhnya menutup mata bagi yang tak bersuara. Aku pernah membaca di buku pelajaranbahwa manusia butuh makan untuk hidup. Tapi yang kulihat dari balik jendela waktu kecil, mereka tidak sekadar lapar. Mereka haus kasih, haus pengakuan, haus keberadaan.
Mereka datang seperti bayangan, dan pergi tanpa bekas. Sama seperti doa-doa yang mungkin tak pernah selesai terucap. Tapi mereka tak pernah mengambil lebih. Tak pernah merusak apa pun. Mereka datang hanya dengan tubuh ringkih dan tatapan yang tidak meminta, hanya berharap.Dan itu cukup membuatku bertahan. Meski tidak lagi tinggal di kampung. Meski kehidupan di kota membuat segala hal serba terburu-buru, aku tetap menyisihkan sejumput nasi setiap malam. Karena aku percaya, kebaikan itu bukan tentang jumlah, tapi tentang niat. Tentang tidak membiarkan yang lapar menjadi tak terlihat.
Kadang aku merasa seperti orang bodoh. Menaruh sepiring nasi di tempat yang mungkin tidak akan disentuh siapa-siapa. Tapi ada malam-malam ketika nasi itu hilang. Atau tinggal sedikit. Dan malam-malam itu, aku tidur dengan lega.Karena meski tak tahu siapa yang datang, aku tahu: Tuhan masih berjalan di bumi ini. Dalam wujud yang tak kita kenal. Dalam bentuk yang tak selalu bersih dan wangi. Tapi nyata.
Semenjak itu, aku mulai menaruh sendiri sepiring nasi, diam-diam, di belakang rumah kontrakan kami. Tak banyak. Hanya satu takaran kecil. Kalau ada remah tempe atau sisa sayur, kutaruh juga.Kadang dimakan kucing. Kadang bersih tanpa jejak. Kadang tetap utuh sampai pagi. Tapi aku tidak peduli.Aku hanya tak ingin kehilangan Tuhan, dalam wujud paling sederhana.Beberapa tahun kemudian, saat aku pulang kampung setelah merantau, aku melihat Mak duduk di dapur sendirian. Wajahnya sudah lebih keriput, rambutnya sepenuhnya putih.
“Aku sering mimpi Tuhan datang, Le,” katanya pelan. “Dia lapar, tapi tidak bisa masuk rumah siapa-siapa. Semua pintu terkunci. Termasuk pintuku.”
Aku menggenggam tangannya. “Tuhan pasti mengerti, Mak.”
Dia mengangguk, tapi matanya tetap basah.Malam itu, kami kembali meletakkan sepiring nasi di bawah pohon jambu.Beberapa minggu kemudian, kabar datang: lelaki tua yang dulu sering mencuri nasi itu meninggal di kolong jembatan. Tidak ada keluarga. Tidak ada nama lengkap. Hanya dicatat sebagai ‘orang tak dikenal’.Berita itu hanya berlangsung sehari. Lalu hilang. Tak ada yang ingat.Tapi malamnya, aku kembali meletakkan sepiring nasi. Kali ini dengan sepotong telur dadar.
Aku tahu, lelaki tua itu mungkin tak sempat tahu bahwa nasi yang ia makan dulu disebut ‘nasi untuk Tuhan’. Tapi aku percaya, ia adalah salah satu wujud Tuhan yang datang ke dunia dengan tubuh lemah dan perut kosong.Dan aku percaya, ketika kita berhenti memberi makan satu sama lain, mungkin itulah saat Tuhan benar-benar pergi.
Kini, aku tinggal di kota besar. Hidup sederhana sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gaji pas-pasan, waktu sempit. Tapi setiap malam, aku tetap menaruh sepiring kecil nasi di teras kos-kosan. Beberapa tetangga mencibir. Ada yang bilang aku aneh. Tapi aku sudah tidak peduli.
Aku tidak sedang memberi makan Tuhan. Aku hanya sedang menjaga kenangan dan berharap jika suatu hari nanti aku yang kelaparan, ada seseorang yang masih percaya bahwa Tuhan mungkin datang dengan tangan gemetar dan wajah kotor.Kita saja yang terlalu suci untuk menyadarinya.
*) Image by istockphoto.com