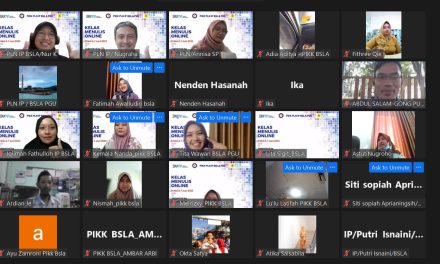Aku tak pernah berambisi hidupku menjadi penting. Cita-citaku cuma satu: pulang kerja tanpa harus ngobrol dengan siapa pun, rebahan di sofa tua kesayanganku sambil nonton berita yang memuakkan, lalu tidur dengan harapan mimpi buruk tak datang. Aku, karyawan rendahan di kantor pajak, adalah spesies yang sudah berdamai dengan kehampaan. Tapi entah kenapa, semesta memutuskan untuk memberi kekacauan di kehidupanku. Dan itu semua gara-gara lemari. Ya, lemari sialan dari pasar loak.
Hari itu Minggu siang. Aku, seperti biasa, jalan-jalan sendiri. Istriku lagi marah, atau tepatnya marah lagi dan lagi. Alasannya: aku ketahuan melakukan pinjaman online, meski yang kulakukan demi kebaikan, yaitu menutup lubang-lubang keuangan keluarga. Jadi, aku kabur ke pasar loak, berharap ada kedamaian di antara tumpukan barang usang. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya: lemari kayu tua, kakinya pincang, catnya kusam, dan kuncinya sudah karat. Penjualnya bilang, “Ini barang keramat, Mas. Peninggalan bangsawan penyepi di gunung Arjuna.” Aku tertawa. Tapi entah kenapa, aku beli juga.
Mungkin karena mataku nyangkut di pahatan pintunya. Mungkin karena hidupku kosong dan aku butuh hal aneh untuk merasa masih hidup. Atau mungkin aku bodoh. Paling mungkin: semuanya benar.
Aku masih ingat bagaimana sinar matahari siang itu terpantul dari kaca lemari tersebut. Ada bayangan samar di permukaannya, mirip siluet seseorang berdiri jauh di belakangku, tapi aku tak begitu hirau. Meski seharusnya aku curiga saat itu, tapi aku lebih sibuk berpikir bagaimana cara menyelundupkan lemari ke rumah tanpa memicu perang badar dengan istriku.
Saat kubawa pulang, istriku histeris. “Rumah ini udah kayak kapal pecah! Kau bawa lagi sampah antik macam itu?” katanya sambil berdiri di depan pintu, kakinya ngetap-ngetap seperti sedang ngitung dosa suaminya.
Aku bohong, tentu saja. “Ini investasi, Dik. Nanti nilainya bisa naik. Barang langka.”
Istriku mungkin sedang lelah, atau lagi malas ngomel, atau mungkin percaya bahwa lemari itu suatu saat bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah ketika dijual lagi. Ia seperti menerima begitu saja, meski dengan wajah merengut.
Aku berdiri di depan kaca lemari itu cukup lama, menatapnya seperti menatap lawan bicara yang keras kepala. Aku mengelilinginya, mengetuk-ngetuk kayunya, membuka dan menutup pintu hanya untuk memastikan tidak ada jebakan tikus atau kecoak mati. Tapi yang kutemukan cuma bau kayu tua dan rasa aneh, seperti ditatap oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tanpa pikir panjang, barang-barangku yang tak jelas dan tak punya tempat kupindahkan ke lemari itu.
Malam pertama. Seharusnya seperti biasa: kopi sachet murahan, lampu temaram, istriku yang tidur lebih cepat dari ayam. Tapi tidak malam itu. Dari kamar, aku dengar suara berderit, keras, seperti kayu tua yang dipaksa bicara. Lalu suara: gedor. Lemari itu bergoyang-goyang. Seperti ada sesuatu yang bernyawa di dalamnya.
Aku pikir itu tikus. Atau hantu. Atau akalku sendiri yang mulai konslet. Tapi aku tetap buka pintu lemari. Dan yang kulihat bukan baju, bukan celana dalam, bukan tikus, bukan pula hantu.
Dari dalam lemari itu muncul makhluk tinggi menjulang, mengenakan semacam baju besi mengilap, matanya menyala merah redup, tubuhnya nyaris menyentuh langit-langit kamar. Dia menatapku seperti aku yang aneh.
“Siapa kau?” aku teriak. Istriku bangun, dan tentu saja kaget.
Makhluk itu… alien itu. Ya tak salah lagi, alien. Mungkin ini yang dinamakan alien humanoid seperti di film-film. Ia melangkah sambil menyibak debu dari bahunya seolah baru bangkit dari tidur panjang.
“Kenapa kaget? Aku Priktarx. Diplomat antargalaksi dari Arktheron,” ucapannya datar. Seolah aku tahu planet itu seperti tahu tentang bulan atau matahari.
Ia sepeti bercanda. Tapi wajahnya benar-benar serius saat mengucapkan itu.
***
Hidupku berubah. Bukan jadi lebih baik. Bukan juga jadi lebih buruk. Tapi jadi semacam film komedi buruk yang lucu. Priktarx menolak masuk kembali ke lemari. Katanya terlalu sempit untuk “pikiran multidimensional”nya. Sekarang dia tinggal di rumahku. Menikmati sofa kesayanganku. Kadang duduk-duduk di dapur. Di ruang tamu. Bahkan di kamar mandi.
“Tapi aku tak mengundangmu,” gertakku, saat berkali-kali meminta dia kembali ke alamnya.
“Aku tak butuh undangan,” jawabnya santai sambil melangkah ke ruang tamu, lalu mengambil koran yang belum sempat kubaca.
Dia habiskan semua kopi di dapur. Kopi kesukaanku. Dari yang rasa cappuccino sampai rasa alpukat. Dia juga nonton TV nonstop. Semua saluran. Dari sinetron, talk show, dan iklan sekaligus. Dia bilang itu cara tercepat memahami manusia.
“Manusia terlalu rumit,” katanya dengan wajah penuh rasa heran. “Mengapa manusia senang memamerkan tangisan, bahkan dalam kondisi damai sekali pun? Dan kenapa benda bernama ‘detergen’ itu sepertinya bisa menyelamatkan segalanya, mulai dari noda kopi sampai pernikahan yang hancur?”
Aku hanya bisa menghela napas ketika dia mulai meniru gaya presenter televisi, memproklamirkan dirinya sebagai pembawa acara Galaksi Disko.
Istriku? Ya Tuhan, aku tak tahu apa yang dia lakukan pada otaknya. Sekarang dia jadi pengagum Priktarx. Masak khusus untuknya. Menyetrika jubahnya. Menyuruhku minggir dari sofa demi “Tamu Penting dari Langit” itu. Aku merasa jadi suami kedua. Bahkan kadang, aku curiga, aku hanya hewan peliharaan di rumah ini.
Priktarx mulai keluar rumah. Bertamu ke tetangga. Anak-anak takut. Mereka panggil dia “Monster Lampu Merah” karena matanya selalu menyala. Beberapa tetangga mengira aku menyewakan rumah ke aktor cosplay. Bahkan ibu penjual sayur keliling menyebar gosip bahwa aku terlibat sekte sesat. Aku jadi bahan pembicaraan. Padahal aku cuma korban.
Puncaknya, Ketua RT mengajakku bicara. Pelan-pelan, sopan, tapi penuh tekanan. “Pak, kami tidak melarang kreativitas, tapi warga jadi resah,” katanya. Aku hanya bisa mengangguk sambil berharap bumi segera meledak. Sebab bagaimana aku menjelaskan bahwa yang tinggal di rumahku bukan seniman performans, tapi alien humanoid dengan obsesi pada deterjen?
***
Suatu malam, aku mendapati Priktarx berdiri di depan cermin dengan jas kantorku yang sudah kutinggalkan sejak 2012, dikenakan terbalik, lengkap dengan sepatu boots istriku.
“Aku menyerap budaya manusia,” katanya sambil berpose. “Ini gaya pemimpin.”
Aku ingin tertawa, tapi terlalu lelah. Beberapa hari kemudian, anak-anak mulai meniru gayanya itu, mengambil jas ayahnya masing-masing. Kompleks kami dipenuhi bocah dengan pakaian absurd dan nyanyian aneh: “Blender itu roh, listrik itu dewa.”
Dan parahnya, dia mulai bicara soal reformasi sosial. Katanya, manusia butuh “pengarahan ulang struktural”. Dia mencorat-coret dinding dengan bagan rumit, ya semacam hierarki kosmik antara manusia, kulkas, dan lampu belajar. Istriku terpesona, mencatat setiap omong kosongnya.
Dan Priktarx, dia sungguh terobsesi dengan listrik. Duduk menatap stopkontak selama berjam-jam. “Di planetku, energi adalah kesadaran,” katanya. “Sedangkan kalian memperlakukannya seperti pelayan.”
Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah tagihan listrik bakal melonjak drastis bulan depan. Tapi dia seolah mengerti pikiranku. Priktarx menawarkan lalu memutuskan sendiri untuk “membantu” perekonomian rumah tangga kami.
Dia memamerkan cara dalam membantu kami. Dia menciptakan sebuah alat aneh dari barang-barang di rumah: blender rusak, antena televisi, dan panci bolong. Dengan alat itu, dia mulai menarik energi dari lingkungan sekitar.
Dia menyalakan alat ciptaannya, tapi lampu-lampu jalanan pada padam, sinyal ngadat dan televisi di rumah tetangga berhenti berfungsi. Seluruh kecamatan mengalami pemadaman listrik total. Dari jendela rumah, aku bisa melihat kegelapan menyelimuti lingkungan.
“Ini sangat efisien,” ujarnya bangga sambil menyerahkan setumpuk uang yang entah dia dapat dari mana.
Tanpa kami sadari, di luar kekacauan mulai terjadi. Suara sirene polisi dan teriakan panik di kejauhan mulai terdengar. Keributan menjalar dengan cepat. Bunyi kentongan dan alarm peringatan bahaya bersahutan. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di depan rumahku tanpa aba-aba. Aku tak tahu kenapa mereka tahu bahwa semuanya bersumber dari rumah kami.
“Ini ulahmu, kan? Monster itu tinggal di sini!” teriak seorang dari mereka, lelaki muda dengan badan penuh tato, sambil menendang pintu rumah.
“Kembalikan listrik kami!” sela seorang lainnya dengan wajah merah padam.
“Ya, kembalikan juga sinyal kami!” sambung yang lain lagi.
“Kembalikan uang kami! Kau yang menariknya, kan?” tambah seorang ibu di tengah kerumunan.
Istriku ketakutan dan menangis, memohon agar aku melakukan sesuatu. Setidaknya meredakan amarah massa. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan kepada mereka tentang makhluk entah berantah yang aku sendiri tak bisa memahaminya?
Di tengah kepanikan itu, Priktarx tetap tenang. “Mereka tidak mengerti,” ucapnya sambil memegang alat buatannya yang memancarkan nyala listrik. “Aku hanya ingin membantu planet ini memanfaatkan energi dengan lebih baik.”
“Membantu? Kau mau membuat hidupku hancur! Kau telah merugikan mereka. Mereka akan menyeret kita ke penjara! Atau mengamuk dan memukuli kita sehingga kita jadi bubur,” ucapku sambil menahan geram.
Priktarx menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu menjawab, “Mungkin aku salah membaca kebiasaan spesiesmu. Tapi kau harus tahu, aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu.” Sebelum aku sempat membalas, dia melangkah ke halaman, menghadapi kerumunan dengan postur tegak.
“Aku hanya meminjam sedikit. Boleh-boleh saja, kan?” lanjutnya dengan suara yang penuh percaya diri.
Ketegangan massa malah semakin menjadi, dan aku hanya bisa menatap, berharap keputusannya tidak membawa bencana lebih besar. Namun semua sudah terlanjur. Amarah massa tak terbendung. Rumah kami dilempari batu, kayu, dan benda-benda keras lainnya oleh orang banyak. Begitu juga kami, tak lepas dari sasaran amuk.
Beruntung serombongan polisi segera datang. Mereka melepaskan tembakan peringatan. Suasana yang sebelumnya kacau, dengan cepat bisa diatasi dan bisa dibicarakan baik-baik dengan kerumunan. Polisi meminta penjelasan tentang “makhluk aneh” ini. Aku mencoba menjelaskan sebisanya.
Akhirnya kami sepakat agar Priktarx tak di sini lagi.
“Kau harus pergi,” kataku setelah massa reda. Priktarx terdiam. Untuk pertama kalinya dia tampak sedih dan seperti anak penurut.
“Aku pikir kita berteman,” ucapnya sendu.
“Teman tidak membuat hidup temannya jadi berantakan.”
Dia mengangguk pelan, lalu berjalan menuju lemari. Sebelum masuk, dia menoleh padaku. “Kau manusia yang menyenangkan, tapi juga unik. Semoga hidupmu lebih tenang setelah aku pergi.”
***
Pagi berikutnya, aku merasa lega. Rumah kembali sunyi, tanpa suara langkah kaki jangkung yang datang dari entah berantah itu. Istriku mulai bersikap normal. Atau pura-pura. Aku tak peduli.
Tapi ketika malam tiba, aku tidak bisa tidur. Sofa terasa terlalu sepi. TV terlalu diam. Tidak ada suara berderit, tidak ada kejutan absurd dari alien itu. Untuk pertama kalinya aku merasa sendirian. Bukan sendiri yang nyaman, tapi sendiri yang sepi. Seolah rumah ini kehilangan gravitasi konyol yang selama ini diam-diam mengikatku.
Semacam ada perasaan aneh, atau rasa penasaran. Aku ingin tahu Priktarx. Kudekati lemari itu. Kutempelkan telingaku ke kacanya yang agak buram, barangkali ada sisa-sisa Priktarx di dalam.
“Energi tak pernah hilang. Hanya berubah bentuk. Sampai jumpa, manusia pelik,” suara yang seakan dari kejauhan, tapi terasa begitu dekat. Di dalam lemari. []
*) Image by istockphoto.com